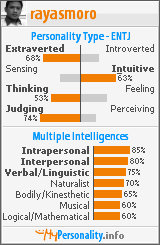Dokter & Cah Angon
(kebangkitan pilonesia)
Sejarah mencatat ditahun 1908 (tepatnya 20 Mei 1908) terlahir sebuah organisasi yang dijadikan tonggak kebangkitan bangsa ini. Organisasi itu bernama Boedi Oetomo, sebuah organisasi pergerakan yang di didirikan oleh kaum cendekia untuk memajukan pendidikan, begitulah pada mulanya sebelum organisasi tersebut terjun secara aktif di bidang politik.
Yang menarik adalah, organisasi Boedi Oetomo tersebut (yang dijadikan titik tonggak kebangkitan bangsa, bahkan tanggal 20 Mei ditetapkan dan diperingati sebagai Hari kebangkitan Nasional) didirikan oleh para dokter. Jadi ternyata semangat kebangkitan bangsa ini terlahir tidak dari tangan dukun beranak, bukan juga dari paranormal, birokrat, teknokrat, atau lainnya, tapi terlahir dari tangan para dokter.
Para dokter inilah yang menolong 'persalinan' dan lahirnya kembali semangat kebangsaan, nasionalisme indonesia lahir ditangan dokter. Sebuah prosesi kelahiran yang sudah semestinya. Di tangan dokter sebuah persalinan secara medis tentu lebih save, karena memang merekalah ahlinya. Lain jika prosesi kelahiran dilakukan oleh dukun beranak. Kemungkinan terjadi infeksi dan kegagalan tentu lebih besar. Apalagi jika yang menangani persalinan adalah teknokrat, seniman atau penulis, akan lebih parah akibatnya. Artinya kelahiran semangat nasionalisme Indonesia lahir dari tangan yang tepat, dari ahlinya; Dokter!
Lebih jauh lagi, Dokter adalah manusia yang telah mempelajari anatomi tubuh manusia, mempelajari tentang berbagai macam penyakit dan gejalanya, sehingga mereka mampu membuat diagnosa-diagnosa. Kalau begini berarti sakitnya ini, obatnya ini dan ini. Kalau begitu berarti sakit itu, obatnya itu dan itu.
Masalahnya sekarang adalah semua orang mengklaim dirinya sebagai Dokter, tapi tidak memiliki kemampuan diagnosa atas persoalan bangsa, tidak memiliki jiwa melayani, yang dimiliki hanyalah ideologi kepentingan yang sempit.
Berikutnya, yang menarik dari Boedi Oetomo adalah bahwa organisasi pergerakan ini memulai gerakannya di bidang pendidikan. Jika bangsa ini ingin maju maka bangsa ini perlu semakin banyak kaum cendekia. Boedi Oetomo itu berasal dari kata 'budi' dan 'utama', artinya berbudi pekerti luhur. Memiliki attitude yang baik. Berjiwa besar. Menyayangi sesama dan tidak pernah menghalalkan pertikaian antar manusia. Lalu apa yang terjadi sekarang? Para kaum cendekia kita justru asik menyusun barisan untuk kepentingan gerombolannya, mereka membuat skenario-skenario perpecahan, mereka ramai-ramai masuk dalam sekat-sekat politik dan kecendikiawanannya tertutup oleh tirai fanatisme kelompok. Dan lihat betapa tragis nasib dunia pendidikan kita, Undang-undang memaklumatkan 20% APBN untuk pendidikan tapi bagaimana realitanya? Banyak sekolah-sekolah yang roboh, fasilitas sekolah sangat minim bahkan banyak yang seperti kandang ayam dan guru-guru tidak dihormati dengan memberikan penghargaan yang layak. Oalaaahhh...
Saya jadi ingat Cak Nun dan Kyai Kanjeng ketika mengupas lagu 'ilir-ilir'nya sunan ampel. Di syair lagu sang sunan itu ada lirik yang mengatakan : "...bocah angon, bocah angon, penekno blimbing kuwi. lunyu-lunyu penekno kanggo sebo mengko sore...". Apapun persepsi anda tentang buah blimbing yang berkikir lima, tapi yang berhak memanjatnya adalah bocah angon alias penggembala, bukan jendral, teknokrat, budayawan ataupun kyai. Siapapun yang memanjat harus memiliki jiwa penggembala, harus mampu mengayomi dan melayani.
Jelas sekarang, tidak penting siapa yang memimpin negeri ini, dari profesi apapun, datang darimanapun, dari suku apapun, apapun agamanya, ia haruslah memiliki predikat sebagai bocah angon, penggembala. Yang mampu melayani dan mengayomi rakyatnya.
20 mei 2008













.jpg)