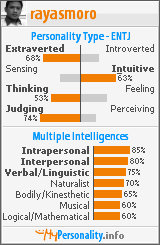ADA CINDERELA DI KEPALAKU
Cerpen Ray Asmoro
Sehari sebelum hari ini, jam ini, persis tiga tahun yang lalu, aku menemukannya di pojok senjakala, di bawah lampu temaram, ketika gerimis datang, tanah-tanah becek. Mendung tebal terlihat di matanya yang bulat dan menghiba.
“Rengkuhlah aku, pahlawanku” katanya lirih, seolah energinya hanya cukup untuk mengucapkan kalimat itu, lalu jatuh pingsan.
Aku angkat gadis belia itu dari lumpur. Menidurkannya di atas ranjang dengan mimpi-mimpi yang tak pernah usai. Tentang masa kanak-kanak yang selalu indah untuk dikenang, tentang masa depan yang selalu indah dalam angan-angan.
Ketika aku terbangun esoknya, Matahari sudah cukup jauh meninggalkan garis cakrawala. Sinar cemerlangnya menembus kaca jendela kamar, menyilaukan mataku. Aku segera bangkit untuk menghadapi kenyataan hari ini. Dan…
Oo, aku tak menemukan gadis itu diatas ranjang!
Aku terdiam sejenak. “Kalau engkau telah pergi, bahkan tanpa sedikitpun pesan, semoga engkau selalu berada ditempat yang penuh rahmat” gumamku dalam hati.
Aku segera mencoba melupakannya. Menganggapnya sebagai bagian dari mimpi burukku. Tetapi ketika aku keluar dan turun untuk mengambil minuman, aku lihat berbagai hidangan tersaji di atas meja makan dan seorang wanita duduk dikursi. Wanita yang berbungkus kemeja putihku, pemberian Diana, perempuan yang hinggap disalah satu sisi belahan dadaku dengan sebuah komitmen yang masih rawan.
Kancing pertama dan kedua dibiarkan terbuka. Wajahnya bercahaya, matanya berbinar-binar, keanggunan yang sempurna. Cerahnya sinar pagi pun tersaingi.
“Engkau Cinderela?” tanyaku dalam ketergagaban.
Ia menatapku, rambutnya yang hitam pekat sebahu bergerai. Lalu ia lemparkan sebuah senyum yang tak bisa aku tangkap maknanya.
“Waktunya makan pagi. Aku akan melayanimu” katanya kemudian.
Ia menjemput dan membimbingku duduk di kursi, dihadapan hidangan hangat yang tersaji. Aku yang masih bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana pendek, patuh begitu saja pada kehendaknya. Ia perlakukan aku seperti bayi. Seolah mengusap ingus sendiripun aku tak bisa. Sebuah perlakuan yang sebenarnya tak pantas bagi lelaki usia tiga puluhan. Tapi aku menikmatinya walaupun beribu-ribu pertanyaan tumpang tindih dalam kepalaku dan tak bisa aku muntahkan. Kenyataan ini terlalu sedap untuk dilewatkan.
Ku teguk segelas air pelepas dahaga. Ku telan segala apa yang disuapkan kedalam mulutku. Sungguh, camar-camar yang genit dan bebatuan karang yang angkuh akan patah hati, andaikata menyaksikan semua ini.
Belum usai ketergagabanku, satu lagi suguhan yang hampir saja menghentikan aliran darah dan denyut jantungku. Ketika ia dekatkan wajahnya sambil menatap mataku. Seribu helai rambutnya, ujungnya menyentuh dadaku yang telanjang, menciptakan sensasi tersendiri. Lalu bibirnya menyentuh bibirku dan seketika darahku mengalir deras, jantungku berdegub kencang bertalu-talu. Jasadnya lekat di jasadku. Aku menggigil. Buliran keringat dingin terbit dari pori-pori kulitku satu per satu. Tiba-tiba aku merasa seperti berada diatas kuda pacuan yang perkasa ditengah-tengah savana. Ku tarik tali kekangnya, ku lecut pantatnya, aku terguncang-guncang diatasnya.
Ia membawaku menjelejahi surga bumi. Semakin lama ku pacu, semakin aku tak mengerti dimana titik permulaannya. Tapi aku tak lagi peduli. Aku hanya ingin tahu dimana ujung perjalanan ini. Maka ku pacu dan terus ku pacu. Aku terguncang-guncang diatasnya. Sekelebat, aku melihat bayangan ibu, adik perempuan dan beberapa perempuan yang pernah memberikan ombak dan pantai tempat kapalku berlabuh. Ya, hanya sekelebat dan tak pernah ku sesali, lalu...
Oh, inilah ujung dari perjalanan ini! Ternyata semuanya berawal dari meja makan dan berakhir di tempat yang sama. Aku mendapati jasad kami diatas meja. Seperti dua ekor kalkun bakar bumbu kecap pedas. Kami mendesis-desis, mengatur napas. Saling pandang dan tersenyum. Tuntas sudah semua hidangan yang tersaji. Semua cita-rasanya telah kami isap bersama-sama tanpa sisa. Kami telah membuat kesan yang indah dalam diri kami masing-masing. Tiada sedikitpun cela.
Begitulah pada mulanya.
Esoknya pengalaman itu terlulang kembali dengan menu hidangan yang berbeda tetapi sama lezatnya. Aku tidak punya pilihan lain kecuali menikmatinya. Ia mengajari aku bagaimana memberi arti pada sebuah sentuhan atau isyarat sekalipun.
Pada hari ketiga, setelah menyantap semua hidangan, tiada bersisa seperti hari hari sebelumnya, tiba-tiba ia berucap “Aku harus pergi.” katanya.
“Aku tak bisa lebih lama lagi disini” imbuhnya.
“Berikan satu alasan padaku untuk bisa melepas kepergianmu dengan kerelaan” sergahku.
“Kau belum mengenalku”
“Aku? Bukankah tiga hari telah kita lewati bersama dengan sangat berkesan? Bukankah selama ini kita bahagia?”
“Kau tidak kenal aku”
“Aku kenal. Aku tahu setiap lekuk tubuhmu. Bahkan aku tahu berapa jumlah tahilalat yang kau punya.”
Kami terdiam sejenak. Seketika suasana menjadi hening dan beku. Aku memandanginya secermat mungkin. Ia menatap jauh kedepan seolah tidak sedang berada dalam ruang yang bersekat tembok semen. Tidak sedikitpun gerakan kulihat. Seperti patung lilin tanpa nyawa. Jasad tanpa rasa. Lalu tanganku bergerak hendak menyentuh pipinya. Aku ingin meyakinkan diriku sendiri, namun ia menampiknya.
“Aku ingin sendiri. Tinggalkan aku sendiri disini. Please…” katanya pelan.
Ada sesuatu yang mendorongku untuk bangkit dan meninggalkan ruang makan. Tapi apa sesuatu itu, aku tidak pernah tahu. Perlahan aku meninggalkannya ke ruang atas. Aku berdiri dibalik jendela memandang jalanan di bawah sana. Banyak kendaraan bermotor mondar-mandir, orang-orang lalu-lalang di trotoar, beberapa ada yang bergerombol hendak menyeberang jalan. Tidak ada yang istimewa.
Cukup lama aku mematung di sana, hingga tiba-tiba aku melihat seseorang menunggang kuda dan berhenti tepat didepan pintu rumahku. Tidak bisa ku lihat wajahnya. Kepalanya tertutup topi baja, hanya bagian mata, hidung dan mulutnya saja yang berlubang. Bajunya juga dari lempengan baja lengkap dengan rumbai-rumbai dan jubah hitamnya, seperti ksatria atau panglima perang kekaisaran Romawi jaman dulu yang sering ku lihat di film. Di pinggangnya terselip sebilah pedang panjang. Dalam hati aku mengagumi kegagahannya.
Sesaat kemudian aku melihat Cinderelaku dari pintu rumahku, melompat naik ke punggung kuda yang ditunggangi ksatria itu. Aku cemburu. Ya, kata itulah yang paling pantas untuk menggambarkan perasaanku. Bahkan aku merasa patah hati ketika ksatria itu menarik tali kekang kudanya. Celakanya, aku tidak mampu berbuat apa-apa.
Cinderelaku masih sempat memandang kearahku. Tangan kanannya memeluk pinggang ksatria itu, sementara tangan kirinya melambai kearahku sambil berucap “Terimakasih, pahlawanku!” lalu mereka segera berlalu. Cinderela telah dijemput Sang Pangeran pujaan hatinya. Dan aku, hanya seorang lelaki yang kehilangan. Kenyataan pahit memang.
* * *
Sehari sebelum hari ini, jam ini, persis tiga tahun yang lalu, aku menemukannya dipojok senjakala, dibawah lampu temaram, ketika gerimis datang, tanah-tanah becek dan mendung tebal terlihat di matanya yang bulat dan menghiba.
 Sudahlah, aku telah melupakannya. Walaupun tidak benar-benar lupa. Ada saat-saat aku menghadirkannya dalam kenangan. Ini jadi rahasia kecilku. Tidak pernah kuceritakan kisah ini pada siapapun, juga pada istriku. Bukankah setiap orang selalu menyimpan rahasia-rahasia kecil yang tak perlu dibagi? Dan malam ini aku sudah batalkan semua janji. Aku harus segera pulang. Diana sudah menunggu. Ia masak spesial. Pasti ia sudah mengganti taplak meja makan, menyalakan lilin diatasnya dan menyemprot ruangan dengan pengharum beraroma melati. Ia pasti juga sudah mengenakan gaun hitam panjangnya, dengan belahan agak lebar dibagian dada, yang ku belikan tempo hari. Hari ini ulang tahun pertama pernikahan kami. Aku akan bersikap romantis malam ini. Sebelum pulang aku harus mampir ke toko bunga, membelikan seikat mawar kesukaannya.
Sudahlah, aku telah melupakannya. Walaupun tidak benar-benar lupa. Ada saat-saat aku menghadirkannya dalam kenangan. Ini jadi rahasia kecilku. Tidak pernah kuceritakan kisah ini pada siapapun, juga pada istriku. Bukankah setiap orang selalu menyimpan rahasia-rahasia kecil yang tak perlu dibagi? Dan malam ini aku sudah batalkan semua janji. Aku harus segera pulang. Diana sudah menunggu. Ia masak spesial. Pasti ia sudah mengganti taplak meja makan, menyalakan lilin diatasnya dan menyemprot ruangan dengan pengharum beraroma melati. Ia pasti juga sudah mengenakan gaun hitam panjangnya, dengan belahan agak lebar dibagian dada, yang ku belikan tempo hari. Hari ini ulang tahun pertama pernikahan kami. Aku akan bersikap romantis malam ini. Sebelum pulang aku harus mampir ke toko bunga, membelikan seikat mawar kesukaannya.
[Jkt, 30.09.02]










.jpg)