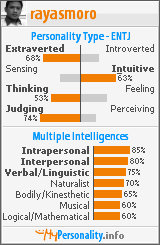PENGAKUAN DOSA
(cerpen Ray Asmoro)
Seorang pria dengan piyama ungu, berdiri di sudut kamar hotel yang redup, memandang keluar jendela. Suasana di luar terlihat sepi, jalanan basah, hujan masih rintik-rintik. Ia menghela napas. Satu tarikan panjang dan sebuah kepuasan sudah diteguknya. Habis. Kemudian ia berpaling.
Ellizabeth masih terbaring di atas ranjang. Ia tercengang melihat kekasihnya berdiri di sana dengan sebuah pistol dalam genggamannya. Lalu ia bangkit sembari menutupi tubuhnya yang putih mulus itu dengan selimut. "Jangan bercanda seperti itu, Morgan," katanya ketika menyadari moncong pistol itu mengarah tepat di keningnya.Morgan tersenyum. Senyum yang begitu akrab di mata Ellizabeth."Aku mencintaimu, Beth. Dan malam ini kamu sungguh luar biasa," ujar Morgan lirih.Lalu Dor! Dor! Dor!
Tiga butir timah panas melesat, menembus dahi, pangkal leher dan uluh hati Ellizabeth. Tiada terelakkan. Sayup-sayup seperti terdengar alunan orkestrasi musik duka-cita, seiring dengan rubuhnya jasad Ellizabeth pada kematian yang tidak pernah dibayangkannya akan datang dengan cara seperti itu. Bahkan ia tak sempat mengucapkan kata-kata perpisahan kepada Jacky, anjing pudel kesayangannya.
Cklek!
Morgan mematikan televisi. Keringat mengucur deras dari setiap pori-pori tubuhnya. Badannya gemetar. Ketakutan, kebingungan, ketidaktahuan, semua tumpang tindih dalam rongga dadanya, setelah melihat sebuah adegan pembunuhan di televisi.Apa yang terjadi pada Faradina, Ivonne dan Ayumi, terjadi juga pada Ellizabeth malam ini. Persis! Tiga luka tembak bersarang di dahi, pangkal leher dan ulu hati. Pembunuhnya selalu meninggalkan sekuntum mawar merah di dada mereka.
Mengapa perempuan-perempuan cantik, muda belia, yang pernah memberinya kebahagiaan selalu menghadapi kematian yang sama? Morgan tidak segera bangkit dari sofa. Wajahnya menampakkan ekspresi kesedihan yang mendalam. Air mata menetes dari kantung matanya sambil sesenggukan. Nampak cengeng bagi laki-laki usia tiga puluh lima. "Ellizabeth," desahnya lirih.Morgan terguncang. Tubuhnya seperti dihantam godam raksasa. Remuk. Ketajaman sembilu seolah mengiris-iris kulit tubuhnya. Kenyerian yang teramat sangat."Oh, Tuhan, apakah aku telah membunuhnya? Tidak mungkin! Bagaimana mungkin aku yang membunuh mereka? Tapi mengapa aku melihat diriku dalam televisi dan melakukan kebiadaban dan kesemena-menaan itu? Bagaimana semua itu bisa terjadi?"
Slide kenangan masa lalunya melintas. Kala itu Morgan baru kuliah pada tingkat pertama di sebuah universitas. Kehangatan keluarganya berantakan lantaran ayahnya serong dengan perempuan lain. Perempuan itu masih belia, cantik dan seksi. Sayangnya, dia seorang pelacur. Secara fisik, dia lebih cocok jadi model iklan atau bintang film. Lalu pertengkaran ayah dan ibunya terjadi setiap hari. Rumah yang dulu damai terasa sesak. Sebuah tamparan keras pernah dirasakan Morgan ketika melawan ayahnya. Dan ujung dari cerita itu, jantung ibunya tidak kuat lagi menahan beban yang menghimpit dadanya. Ibunya meninggal dan ayahnya seperti menemukan kemerdekaan.
Morgan memilih untuk minggat, meninggalkan rumah neraka itu. Sejak itu Morgan kehilangan keriangannya, ia menjadi pendiam dan bersikap aneh. Dendam bersarang di kepalanya.Malam pun berlalu dengan sangat lambat dan nyeri.
Pagi harinya semua media massa kembali mengekspose berita pembunuhan berantai. Dalam siaran televisi, polisi belum bisa mengidentifikasi siapa pelaku pembunuhan itu, karena pelaku tidak meninggalkan jejak. Tidak ada sidik jari. Yang ditemukan hanya sekuntum mawar merah. Polisi tampak kehilangan akal mengusut siapa pelaku keempat pembunuhan itu.
"Pembunuhan ini dilakukan oleh seorang maniak profesional. Kami akan terus melakukan penyidikan dengan seksama, percayakan semuanya kepada kami," begitu dalih polisi ketika ditanya para pemburu berita tentang penyelesaian kasus pembunuhan berantai yang terjadi empat bulan berturut-turut di kota ini.
Morgan terbangun dari tidurnya tanpa secuil mimpi yang berkesan. Ia bangkit tanpa beban perasaan. Seolah tak ada dosa sejumput pun dalam kehidupannya. Lalu ia membuka tirai dan jendela kamar. Udara pagi segar terasa. Sinar matahari yang cemerlang menyilaukan matanya. Morgan memicingkan mata, lalu membuang pandangannya ke arah lain, ke sudut halaman belakang tetangganya. Ia menatap beberapa pot bunga yang hanya beberapa langkah dari kamarnya. Tidak ada pagar yang memisahkan tempat tinggalnya dengan halaman belakang rumah sebelah, dan memberikan keleluasaan pandangannya.Morgan melihat beberapa pot bunga yang ditanami mawar. Ia terkesiap.
Sekuntum mawar terlihat mekar merah merekah. Indah sekali. Morgan memang menyukai mawar. Bahkan ia membuat tato mawar di lengannya. Tapi bukan keindahan mawar itu yang membuatnya terkesiap. Ia melihat beberapa tangkai yang patah atau dipatahkan. Seperti ada yang telah memetiknya dengan paksa. Pemiliknyakah yang memetik mawar itu? Atau orang lain yang jatuh cinta pada mawar itu?
Morgan teringat pada kematian Faradina, Ivonne, Ayumi dan Ellizabeth. Pembunuhnya selalu meninggalkan sekuntum mawar di atas mayat mereka. Pemilik mawar itukah pembunuhnya? Lalu apa motifnya? Morgan tidak menemukan jawabannya. Pemilik rumah sebelah adalah pasangan suami istri yang bekerja. Pagi-pagi mereka sudah berangkat dan pulang pada malam hari. Rutinitas itulah yang mereka jalani setiap hari. Kecuali hari libur. Bahkan saat liburpun mereka sering menghabiskannya di luar rumah. Nonton film atau piknik ke Puncak. Sesekali saja mereka terlihat di rumahnya, sedang bersih-bersih, berkebun dan tentu saja menanam mawar.
Tiba-tiba ada yang melintas dalam kesadaran Morgan. Ia bergegas menyambar baju yang tergantung di pintu kamarnya dan segera keluar rumah. Ia berjalan tergesa-gesa setengah berlari, ayunan langkahnya menuju gereja yang jaraknya cuma satu blok dari tempat tinggalnya. Hampir enam belas tahun lamanya ia tak pernah mengikuti misa. Dulu, ia adalah seorang jemaat yang taat. Entah sebab apa ia lalai selama itu. Yang ia ingat, terakhir kali ke gereja pada saat melepas jenazah ibunya dalam sebuah misa di kota kelahirannya.
Dan hari ini, setelah alpa selama hampir enam belas tahun, spontanitas kesadaran Morgan mengantarkannya ke rumah Tuhan. Di depan bilik yang dibuat secara spesifik, Morgan berhenti, terdiam sejenak dan menarik napas dalam-dalam sebelum berkata-kata."Bapa, aku telah melakukan perbuatan dosa," katanya.
"Apa yang engkau perbuat anakku?" begitu suara dari dalam bilik itu.
"Mulanya aku tidak yakin telah melakukan perbuatan dosa, Bapa."
"Dosa apa yang telah engkau perbuat, anakku?"
Morgan terdiam. Kali ini ia menjadi ragu untuk menceritakan semuanya.
"Katakan apa yang telah engkau perbuat, anakku. Tuhan akan menebus semua dosa-dosa itu dan merahmatimu dengan cahaya kasih."
Morgan semakin ciut dan tidak mampu angkat bicara. Ia merasa terpojok oleh dirinya sendiri, oleh pikirannya yang kusut, oleh bayangan-bayangan keempat wanita yang terbunuh secara tragis.
Morgan menarik napas, ia mengumpulkan seluruh keberanian yang ada di rongga dadanya lalu berkata dengan penuh keyakinan."Bapa, aku telah mencuri mawar milik tetangga."
Puji Tuhan!
(Menteng, 03.10.02)
Dipublikasikan oleh Suara Pembaruan 02.09.2003
Kamis, Juli 19, 2007
Rabu, Juli 18, 2007
Saya seringkali bertanya-tanya (tanpa bermaksud mendeskriditkan siapa-siapa), jadi apa kelak anak-anak yang lahir dan dibesarkan di lokalisasi pelacuran itu? Menjadi pelacur atau mucikarikah? Bisa jadi, karena setiap hari dan setiap saat kehidupan macam itulah yang dilihatnya. Apalagi katanya masa anak-anak adalah masa pertumbuhan dimana setiap yang dilihat, didengar, terekam dan melekat dihati dan pikiran.
Apabila kuping kita dibiasakan mendengar lagu dangdut secara terus menerus, maka yang ada diotak kita, musik adalah dangdut. Dan bila kemudian diperdengarkan musik jazz maka terjadi penolakan dalam diri kita, kita tidak bisa mencerna dan menikmatinya, bahkan jika kita diajak nonton konser Bobby Brown secara gratis pun pasti kita tolak bahkan mencerca dengan kalimat “musik apaan itu?”. Padahal bagi yang menyukai jazz, mereka berpendapat sebaliknya. Maka itulah ada kelompok pecinta dangdut, jazz, country, rock ‘n roll, blues, heavy metal, punk, rap, campursari dan lain-lain. Hanya sedikit orang saja yang bisa menerima segala jenis musik.
Lalu bagaimana dengan anak-anak tadi? Padahal yang paling dekat dengan mereka adalah mucikari dan pelacur, setiap hari hidup diantara mereka. Wajar bila kemudian yang terjadi anak-anak mulai mencuri-curi kesempatan untuk merokok, minum alkohol dan bicara kasar.
Jika bapaknya mucikari, ibunya pelacur, apakah anaknya pasti akan menjadi (maaf) begundal? Pasti kita semua sepakat untuk menjawab “belum tentu!”. Kenyataan yang pernah saya temui, ada seorang pelacur yang sangat tidak ingin anaknya menjadi begundal, ia ingin kelak anaknya menjadi orang bener. Maka ia jauhkan anaknya dari lingkungannya dan memasukkannya ke sebuah pesantren yang setiap hari diajari mengaji, selain sekolah seperti pada umumnya.
Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa lingkungan punya pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan kita. Saya punya gambaran seperti ini. Ibaratkan kita hanya setitik air, apabila air setitik itu diteteskan ke danau maka kita akan lebur menjadi air danau. Apabila diteteskan di laut kita akan lebur menjadi air laut yang asin. Apabila diteteskan di comberan, niscaya kita akan lebur jadi comberan yang kotor dan bau. Maka tidak salah apabila banyak orang berkata, jika ingin jadi orang sukses bergaullah dengan orang-orang sukses, jika ingin pandai bergaullah dengan kaum cendekia.
Dari analogi yang saya kemukakan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan, pertama bahwa kita akan kalah dan lebur pada hal-hal yang lebih kuat dan besar. Lingkungan adalah salah satu kekuatan besar yang melingkupi kita. Kedua, apabila kita hendak menguasai atau memberikan warna pada sesuatu yang lebih besar dari kita atau lingkungan kita, maka kita harus berupaya menjadi yang lebih besar lagi atau kita harus memiliki warna yang lebih kuat dari lingkungan kita tersebut. Ingat, susu sebelanga akan rusak hanya oleh setitik nira.
Sedari kecil saya hidup ditengah-tengah masyarakat petani atau buruh tani, seperti anak-anak dusun yang lain, setiap hari bermain disawah, mencari rumput untuk hewan ternak, membantu menanam padi dan itu berlansung bertahun-tahun. Tidak heran apabila (dulu) hanya satu dua orang saja yang berpendidikan tinggi di kampung saya. Paradigma sukses bagi mereka bahwa satu-satunya cara untuk berhasil adalah harus lebih rajin dan lebih giat mengayunkan cangkul dan bertani sepenuh hati, bukan dengan sekolah tinggi. Kesuksesan itu adanya di sawah, bukan disekolah!
Banyak yang mecibir pada orang tua saya pada saat saya dan kakak saya melanjutkan ke perguruan tinggi, apalagi untuk itu orang tua saya harus merelakan beberapa petak sawahnya dijual untuk biaya kuliah. Orang tua saya berusaha untuk keluar dari paradigma yang “salah” yang ada dimasyarakat itu. Cibiran dan caci maki tak dihiraukan, ia terus melawan arus. Dan itu akan menjadi mustahil jika tanpa belief yang kuat.
Kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Benarkah? Dari sisi karakter mungkin masih ada benarnya. Tapi dari sisi nasib, masa depan dan kesuksesan, saya sama sekali tidak sependapat dengan peribahasa itu. Apakah anak Jendral selalu menjadi Jendral? Apakah anak Dokter pasti menjadi dokter? Apakah anak guru niscaya menjadi guru? Apakah anak buruh tani harus menjadi buruh tani? Tentu tidak, bukan?
Sebagai anak kecil waktu itu, yang terpikir dalam benak saya adalah saya harus menjadi orang sukses, menjadi orang besar, dan tidak mau jadi buruh tani! Bahkan saya harus menjadi kebanggaan tidak saja bagi orang tua dan keluarga tapi juga bagi seluruh masyarakat dusun saya, sehingga semua orang didusun saya terbuka cakrawala pikirannya dan punya semangat untuk maju. Begitulah kira-kira pada mulanya.
Yang terjadi kemudian adalah pemberontakan-pemberontakan kecil-kecilan. Saya ingin baca buku-buku tapi didusun saya tidak ada fasilitasnya. Kalaupun harus beli buku, orang tua saya tidak memiliki anggarannya. Semangat pemberontakan semakin menyala-nyala. Bahkan ketika masa paceklik, kami makan nasi jagung berlauk garam, maka semakin terbakarlah semangat pemberontakan dalam diri saya, bahkan muncul dendam kesumat. Pada saatnya nanti saya dan keluarga saya harus lepas dari himpitan kesusahan seperti itu yang telah bertahun-tahun dirasakan.
Adalah sebuah perjuangan yang sangat berat untuk dapat keluar dari keterkungkungan pengaruh lingkungan. Sama halnya dengan saudara-saudara kita yang terjebak dalam lingkungan yang gemar mengkonsumsi narkoba. Sebagian besar dari mereka adalah kaum terdidik yang sangat faham efek negatif dari narkoba. Sebagaian besar dari mereka bukan tidak mau lepas dari jeratan narkoba. Mereka ingin sekali lepas tapi lingkungan mereka tidak mendukung. Mereka sudah terperangkap, terjerat. Dibutuhkan kekuatan, keyakinan dan tekad besar, lebih besar dari kekuatan pengaruh lingkungan itu untuk dapat keluar dari jeratannya. Jadi, bukannya tidak mungkin, bukan?
Semangat seperti itu pulalah yang menyala-nyala dalam bathin saya. Karena saya tidak mau terus menerus terisolasi dari informasi-informasi yang orang dusun seperti sayapun berhak mendapatkannya. Saya tidak mau selamanya hidup dalam kesempitan yang menghimpit. Saya merasa tidak wajib menjadi buruh tani walaupun orang tua saya hanya petani! Sekarang hanya ada dua pilihan menunggu momentum atau menciptakan momentum untuk melakukan lompatan dan meraih yang lebih baik dalam kehidupan ini. Atau hanya menjadi penonton saja?
Terserah anda.
Apabila kuping kita dibiasakan mendengar lagu dangdut secara terus menerus, maka yang ada diotak kita, musik adalah dangdut. Dan bila kemudian diperdengarkan musik jazz maka terjadi penolakan dalam diri kita, kita tidak bisa mencerna dan menikmatinya, bahkan jika kita diajak nonton konser Bobby Brown secara gratis pun pasti kita tolak bahkan mencerca dengan kalimat “musik apaan itu?”. Padahal bagi yang menyukai jazz, mereka berpendapat sebaliknya. Maka itulah ada kelompok pecinta dangdut, jazz, country, rock ‘n roll, blues, heavy metal, punk, rap, campursari dan lain-lain. Hanya sedikit orang saja yang bisa menerima segala jenis musik.
Lalu bagaimana dengan anak-anak tadi? Padahal yang paling dekat dengan mereka adalah mucikari dan pelacur, setiap hari hidup diantara mereka. Wajar bila kemudian yang terjadi anak-anak mulai mencuri-curi kesempatan untuk merokok, minum alkohol dan bicara kasar.
Jika bapaknya mucikari, ibunya pelacur, apakah anaknya pasti akan menjadi (maaf) begundal? Pasti kita semua sepakat untuk menjawab “belum tentu!”. Kenyataan yang pernah saya temui, ada seorang pelacur yang sangat tidak ingin anaknya menjadi begundal, ia ingin kelak anaknya menjadi orang bener. Maka ia jauhkan anaknya dari lingkungannya dan memasukkannya ke sebuah pesantren yang setiap hari diajari mengaji, selain sekolah seperti pada umumnya.
Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa lingkungan punya pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan kita. Saya punya gambaran seperti ini. Ibaratkan kita hanya setitik air, apabila air setitik itu diteteskan ke danau maka kita akan lebur menjadi air danau. Apabila diteteskan di laut kita akan lebur menjadi air laut yang asin. Apabila diteteskan di comberan, niscaya kita akan lebur jadi comberan yang kotor dan bau. Maka tidak salah apabila banyak orang berkata, jika ingin jadi orang sukses bergaullah dengan orang-orang sukses, jika ingin pandai bergaullah dengan kaum cendekia.
Dari analogi yang saya kemukakan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan, pertama bahwa kita akan kalah dan lebur pada hal-hal yang lebih kuat dan besar. Lingkungan adalah salah satu kekuatan besar yang melingkupi kita. Kedua, apabila kita hendak menguasai atau memberikan warna pada sesuatu yang lebih besar dari kita atau lingkungan kita, maka kita harus berupaya menjadi yang lebih besar lagi atau kita harus memiliki warna yang lebih kuat dari lingkungan kita tersebut. Ingat, susu sebelanga akan rusak hanya oleh setitik nira.
Sedari kecil saya hidup ditengah-tengah masyarakat petani atau buruh tani, seperti anak-anak dusun yang lain, setiap hari bermain disawah, mencari rumput untuk hewan ternak, membantu menanam padi dan itu berlansung bertahun-tahun. Tidak heran apabila (dulu) hanya satu dua orang saja yang berpendidikan tinggi di kampung saya. Paradigma sukses bagi mereka bahwa satu-satunya cara untuk berhasil adalah harus lebih rajin dan lebih giat mengayunkan cangkul dan bertani sepenuh hati, bukan dengan sekolah tinggi. Kesuksesan itu adanya di sawah, bukan disekolah!
Banyak yang mecibir pada orang tua saya pada saat saya dan kakak saya melanjutkan ke perguruan tinggi, apalagi untuk itu orang tua saya harus merelakan beberapa petak sawahnya dijual untuk biaya kuliah. Orang tua saya berusaha untuk keluar dari paradigma yang “salah” yang ada dimasyarakat itu. Cibiran dan caci maki tak dihiraukan, ia terus melawan arus. Dan itu akan menjadi mustahil jika tanpa belief yang kuat.
Kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Benarkah? Dari sisi karakter mungkin masih ada benarnya. Tapi dari sisi nasib, masa depan dan kesuksesan, saya sama sekali tidak sependapat dengan peribahasa itu. Apakah anak Jendral selalu menjadi Jendral? Apakah anak Dokter pasti menjadi dokter? Apakah anak guru niscaya menjadi guru? Apakah anak buruh tani harus menjadi buruh tani? Tentu tidak, bukan?
Sebagai anak kecil waktu itu, yang terpikir dalam benak saya adalah saya harus menjadi orang sukses, menjadi orang besar, dan tidak mau jadi buruh tani! Bahkan saya harus menjadi kebanggaan tidak saja bagi orang tua dan keluarga tapi juga bagi seluruh masyarakat dusun saya, sehingga semua orang didusun saya terbuka cakrawala pikirannya dan punya semangat untuk maju. Begitulah kira-kira pada mulanya.
Yang terjadi kemudian adalah pemberontakan-pemberontakan kecil-kecilan. Saya ingin baca buku-buku tapi didusun saya tidak ada fasilitasnya. Kalaupun harus beli buku, orang tua saya tidak memiliki anggarannya. Semangat pemberontakan semakin menyala-nyala. Bahkan ketika masa paceklik, kami makan nasi jagung berlauk garam, maka semakin terbakarlah semangat pemberontakan dalam diri saya, bahkan muncul dendam kesumat. Pada saatnya nanti saya dan keluarga saya harus lepas dari himpitan kesusahan seperti itu yang telah bertahun-tahun dirasakan.
Adalah sebuah perjuangan yang sangat berat untuk dapat keluar dari keterkungkungan pengaruh lingkungan. Sama halnya dengan saudara-saudara kita yang terjebak dalam lingkungan yang gemar mengkonsumsi narkoba. Sebagian besar dari mereka adalah kaum terdidik yang sangat faham efek negatif dari narkoba. Sebagaian besar dari mereka bukan tidak mau lepas dari jeratan narkoba. Mereka ingin sekali lepas tapi lingkungan mereka tidak mendukung. Mereka sudah terperangkap, terjerat. Dibutuhkan kekuatan, keyakinan dan tekad besar, lebih besar dari kekuatan pengaruh lingkungan itu untuk dapat keluar dari jeratannya. Jadi, bukannya tidak mungkin, bukan?
Semangat seperti itu pulalah yang menyala-nyala dalam bathin saya. Karena saya tidak mau terus menerus terisolasi dari informasi-informasi yang orang dusun seperti sayapun berhak mendapatkannya. Saya tidak mau selamanya hidup dalam kesempitan yang menghimpit. Saya merasa tidak wajib menjadi buruh tani walaupun orang tua saya hanya petani! Sekarang hanya ada dua pilihan menunggu momentum atau menciptakan momentum untuk melakukan lompatan dan meraih yang lebih baik dalam kehidupan ini. Atau hanya menjadi penonton saja?
Terserah anda.
KENAPA TAKUT BERMIMPI ?
“Life is beautiful” adalah salah satu film favorit saya, dibintangi dan disutradarai oleh Roberto Benigni yang dikemas secara komedian dan sangat teateral namun menyuguhkan ironi yang luar biasa pekatnya.
Yang menarik dari film tersebut salah satunya adalah “mimpi” yang disuguhkan sang ayah bagi anaknya agar mampu bertahan dan selamat. Sang anak selalu diberikan impian bahwa yang mereka jalani adalah sebuah permainan untuk mendapatkan hadiah sebuah tank lapis baja seperti impian anaknya.
Dan benar, hidup ini tak lebih dari sekedar permainan, semakin banyak poin yang kita kumpulkan maka semakin besar peluang kita untuk menjadi pemenang. Bukankah kesuksesan besar itu adalah buah dari keberhasilan kita mengumpulkan kesuksesan-kesuksesan kecil? Begitulah kata para motivator.
Sewaktu kecil, kami anak-anak dusun sangat terkagum-kagum jika ada mobil sedan atau truck yang melintas di jalan dusun kami yang penuh bebatuan. Kami akan berlarian dibelakang mobil yang tak mungkin melaju kecang dijalan bebatuan itu, kami hirup bau asap knalpotnya, dan itu suatu kemewahan bagi kami. Jika ada pesawat melintas diatas dusun kami, kami anak-anak kecil berlarian ke halaman lalu berteriak-teriak “Hooy…! Minta uangnya…! Minta Uangnya…!” seolah-olah suara kami terdengar oleh penumpang pesawat yang nun jauh tinggi disana.
Saya seringkali tersenyum-senyum sendiri mengingat hal-hal seperti itu. Kalau dipikir-pikir kenapa kami waktu itu selalu berteriak “Hooy..! Minta Uangnya…!” mengapa kami tidak berteriak “Hooy.. Ajak kami terbang..!”. Mungkin karena kami setiap hari hidup dalam himpitan kemiskinan sehingga uang menjadi segala-galanya. Namun saya ingat betul, walaupun saya salah satu yang ikut berteriak “Hooy..! Minta uangnya..!” tapi entah mengapa dan entah darimana datangnya ada secuil impian dalam benak saya, bahwa suatu ketika saya harus menjadi salah satu orang yang duduk dalam pesawat itu. Ya suatu ketika, harus! Impian yang naïf bagi anak dusun seperti saya.
Bertahun-tahun saya menunggu dan berupaya mewujudkan mimpi kecil itu. Ternyata mimpi kecil itu baru terwujud setalah saya berumur 29 tahun! (saya sudah hijrah dan bekerja di Jakarta). Saat memasuki pintu pesawat saya ingat masa-masa kecil dulu. Begitu pesawat take off dan mulai terbang tinggi, airmata saya menetes. 29 tahun lamanya saya menunggu saat-saat seperti ini! Saya lihat keluar jendela, saya seperti melihat sebuah peta besar dibawah sana. Saya membayangkan saya dan teman-teman saya masa kecil dulu berada dibawah sana bertelanjang dada tanpa alas kaki, berteriak-teriak “Hooy..! Minta Uangnya…!”. Saya juga melihat hamparan awan seperti tumpukan beribu-ribu ton kapas. Oh, akhirnya mimpipun menjadi nyata. I Believe I Can Fly. Subhanallah…
Cerita lain. Saat masih kecil belum ada listrik didusun kami, jalan tidak beraspal dan becek dimusim hujan, hampir tidak ada satupun warga yang memiliki pesawat televisi. Bude yang mengasuh saya seringkali mengajak saya nonton TV di rumah Pak Kades (kepala desa). TV hitam putih 14 inchi dipajang dihalamannya. Suasananya percis orang nonton layer tancap. Baru pada saat saya berusia 4 tahun, bapak saya mampu beli TV (hitam putih) yang menggunakan accu untuk menyalakannya, karena listrik belum ada.
Entah mengapa saya suka dengan acara Aneka Ria Safari dan Selekta Pop (pada saat itu yang ada hanya TVRI) dan Film cerita akhir pekan, apalagi jika bintang filmnya Rano Karno. Saya sangat mengidolakannya semasa kecil. Bahkan jika Rano Karno muncul di acara Film Cerita Akhir Pekan dan saya tertidur dan ibu tidak membangunkannya, maka bisa dipastikan saya akan marah-marah esoknya jika dengar cerita dari teman atau orang lain.
Karena mengidolakan Rano Karno semasa kecil, maka saya punya impian menjadi aktor. Diam-diam seringkali saya ekting sendiri didepan kaca. Saya bisa tiba-tiba sedih dan menangis kemudian saya bicara dan berdialog sendiri, lalu tiba-tiba saya tertawa-tawa.
Saat SMA saya memilih aktifitas teater untuk kegiatan ekstrakurikuler. Begitu juga pada saat kuliah, kegiatan saya di teater semakin menjadi-jadi, bahkan saya pernah membawa kelompok teater saya mengisi 4 episode untuk tayangan di TVRI Stasiun Surabaya (Programa 2). Dan saya berperan sebagai penulis naskah, sutradara sekaligus aktor. Pada saat itu, untuk dapat kesempatan tampil di televisi adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Apalagi kelompok kami belum genap 2 tahun. Maka satu lagi impian kecil saya menjadi kenyataan. Walaupun tidak seideal yang diinginkan.
Banyak impian saya yang telah menjadi kenyataan. Bahkan dahulu saya pernah memimpikan menjadi direktur sebuah perusahaan. Karena dalam bayangan saya jadi direktur itu enak, banyak duitnya, hidupnya menyenangkan. Dan benar impian itupun menjadi kenyataan! Walaupun ternyata tidak seenak yang saya bayangkan sebelumnya karena tugas dan tanggungjawabnya ternyata sedemikian besar.
Saya coba analogikan, semisal anda ditantang untuk memasukkan satu buah bola basket ke dalam keranjangnya maka probabilitas anda dapat memasukkannya adalah 1:1. Tapi jika anda diberikan 10 bola basket untuk dimasukkan ke keranjangya maka probabilitas keberhasilan anda adalah 1:10, bukan? Sekarang coba anda bayangkan bola basket itu adalah impian atau cita-cita anda. Jika anda hanya punya satu impian maka bersiaplah menerima kegagalan karena probabilitasnya rendah, tapi jika anda punya beberapa impian maka bersiap-siaplah menyongsong keberhasilan karena kemungkinan salah satu dari impian anda menjadi nyata.
Saat saya duduk sebagai Head of HR, saya sering melakukan wawancara. Beberapa kali saya bertanya kepada pelamar “apa yang ingin anda capai atau wujudkan dalam kurun waktu 5 atau 10 tahun ke depan?”. Rata-rata mereka kebingungan mencari jawaban. Mungkin juga karena nervous. Tetapi mengapa hampir semua begitu? Namun ada diantara mereka yang menjawab “saya ingin punya pekerjaan tetap dan menikah, pak”. “Hanya itu?” Ia menjawab “kalau keinginan sih banyak pak”. “Coba sebutkan”. “Saya ingin punya rumah sendiri, punya mobil, dan bisa membiayai orang tua berangkat ibadah haji”. “Lalu, apa itu mustahil?”. “Yah, sepertinya tidak mungkin pak. Sekarang saja saya masih baru mencari pekerjaan”.
Impian itu adalah bentuk visualisasi dari keinginan, cita-cita atau tujuan kita. Lha bagaimana bisa sampai pada keinginan atau cita-cita jikalau kita tidak pernah bisa memimpikannya. Tidak pernah mampu memvisualkannya. Bagaimana kita bisa menginginkan dapat mobil jika kita tidak pernah punya gambaran mobil itu seperti apa. Bagaimana kita bisa mendapatkan istri yang cantik, misalnya, jika kita sama sekali tidak punya gambaran tentang kecantikan.
Banyak orang sukses menasehati, untuk berhasil anda harus terlebih dahulu memimpikan keberhasilan itu, kemudian anda harus meyakini bahwa keberhasilan itu bisa diraih, lalu… raihlah. Simpel bukan?
Jadi kenapa takut bermimpi? Bermimpilah!
Yang menarik dari film tersebut salah satunya adalah “mimpi” yang disuguhkan sang ayah bagi anaknya agar mampu bertahan dan selamat. Sang anak selalu diberikan impian bahwa yang mereka jalani adalah sebuah permainan untuk mendapatkan hadiah sebuah tank lapis baja seperti impian anaknya.
Dan benar, hidup ini tak lebih dari sekedar permainan, semakin banyak poin yang kita kumpulkan maka semakin besar peluang kita untuk menjadi pemenang. Bukankah kesuksesan besar itu adalah buah dari keberhasilan kita mengumpulkan kesuksesan-kesuksesan kecil? Begitulah kata para motivator.
Sewaktu kecil, kami anak-anak dusun sangat terkagum-kagum jika ada mobil sedan atau truck yang melintas di jalan dusun kami yang penuh bebatuan. Kami akan berlarian dibelakang mobil yang tak mungkin melaju kecang dijalan bebatuan itu, kami hirup bau asap knalpotnya, dan itu suatu kemewahan bagi kami. Jika ada pesawat melintas diatas dusun kami, kami anak-anak kecil berlarian ke halaman lalu berteriak-teriak “Hooy…! Minta uangnya…! Minta Uangnya…!” seolah-olah suara kami terdengar oleh penumpang pesawat yang nun jauh tinggi disana.
Saya seringkali tersenyum-senyum sendiri mengingat hal-hal seperti itu. Kalau dipikir-pikir kenapa kami waktu itu selalu berteriak “Hooy..! Minta Uangnya…!” mengapa kami tidak berteriak “Hooy.. Ajak kami terbang..!”. Mungkin karena kami setiap hari hidup dalam himpitan kemiskinan sehingga uang menjadi segala-galanya. Namun saya ingat betul, walaupun saya salah satu yang ikut berteriak “Hooy..! Minta uangnya..!” tapi entah mengapa dan entah darimana datangnya ada secuil impian dalam benak saya, bahwa suatu ketika saya harus menjadi salah satu orang yang duduk dalam pesawat itu. Ya suatu ketika, harus! Impian yang naïf bagi anak dusun seperti saya.
Bertahun-tahun saya menunggu dan berupaya mewujudkan mimpi kecil itu. Ternyata mimpi kecil itu baru terwujud setalah saya berumur 29 tahun! (saya sudah hijrah dan bekerja di Jakarta). Saat memasuki pintu pesawat saya ingat masa-masa kecil dulu. Begitu pesawat take off dan mulai terbang tinggi, airmata saya menetes. 29 tahun lamanya saya menunggu saat-saat seperti ini! Saya lihat keluar jendela, saya seperti melihat sebuah peta besar dibawah sana. Saya membayangkan saya dan teman-teman saya masa kecil dulu berada dibawah sana bertelanjang dada tanpa alas kaki, berteriak-teriak “Hooy..! Minta Uangnya…!”. Saya juga melihat hamparan awan seperti tumpukan beribu-ribu ton kapas. Oh, akhirnya mimpipun menjadi nyata. I Believe I Can Fly. Subhanallah…
Cerita lain. Saat masih kecil belum ada listrik didusun kami, jalan tidak beraspal dan becek dimusim hujan, hampir tidak ada satupun warga yang memiliki pesawat televisi. Bude yang mengasuh saya seringkali mengajak saya nonton TV di rumah Pak Kades (kepala desa). TV hitam putih 14 inchi dipajang dihalamannya. Suasananya percis orang nonton layer tancap. Baru pada saat saya berusia 4 tahun, bapak saya mampu beli TV (hitam putih) yang menggunakan accu untuk menyalakannya, karena listrik belum ada.
Entah mengapa saya suka dengan acara Aneka Ria Safari dan Selekta Pop (pada saat itu yang ada hanya TVRI) dan Film cerita akhir pekan, apalagi jika bintang filmnya Rano Karno. Saya sangat mengidolakannya semasa kecil. Bahkan jika Rano Karno muncul di acara Film Cerita Akhir Pekan dan saya tertidur dan ibu tidak membangunkannya, maka bisa dipastikan saya akan marah-marah esoknya jika dengar cerita dari teman atau orang lain.
Karena mengidolakan Rano Karno semasa kecil, maka saya punya impian menjadi aktor. Diam-diam seringkali saya ekting sendiri didepan kaca. Saya bisa tiba-tiba sedih dan menangis kemudian saya bicara dan berdialog sendiri, lalu tiba-tiba saya tertawa-tawa.
Saat SMA saya memilih aktifitas teater untuk kegiatan ekstrakurikuler. Begitu juga pada saat kuliah, kegiatan saya di teater semakin menjadi-jadi, bahkan saya pernah membawa kelompok teater saya mengisi 4 episode untuk tayangan di TVRI Stasiun Surabaya (Programa 2). Dan saya berperan sebagai penulis naskah, sutradara sekaligus aktor. Pada saat itu, untuk dapat kesempatan tampil di televisi adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Apalagi kelompok kami belum genap 2 tahun. Maka satu lagi impian kecil saya menjadi kenyataan. Walaupun tidak seideal yang diinginkan.
Banyak impian saya yang telah menjadi kenyataan. Bahkan dahulu saya pernah memimpikan menjadi direktur sebuah perusahaan. Karena dalam bayangan saya jadi direktur itu enak, banyak duitnya, hidupnya menyenangkan. Dan benar impian itupun menjadi kenyataan! Walaupun ternyata tidak seenak yang saya bayangkan sebelumnya karena tugas dan tanggungjawabnya ternyata sedemikian besar.
Saya coba analogikan, semisal anda ditantang untuk memasukkan satu buah bola basket ke dalam keranjangnya maka probabilitas anda dapat memasukkannya adalah 1:1. Tapi jika anda diberikan 10 bola basket untuk dimasukkan ke keranjangya maka probabilitas keberhasilan anda adalah 1:10, bukan? Sekarang coba anda bayangkan bola basket itu adalah impian atau cita-cita anda. Jika anda hanya punya satu impian maka bersiaplah menerima kegagalan karena probabilitasnya rendah, tapi jika anda punya beberapa impian maka bersiap-siaplah menyongsong keberhasilan karena kemungkinan salah satu dari impian anda menjadi nyata.
Saat saya duduk sebagai Head of HR, saya sering melakukan wawancara. Beberapa kali saya bertanya kepada pelamar “apa yang ingin anda capai atau wujudkan dalam kurun waktu 5 atau 10 tahun ke depan?”. Rata-rata mereka kebingungan mencari jawaban. Mungkin juga karena nervous. Tetapi mengapa hampir semua begitu? Namun ada diantara mereka yang menjawab “saya ingin punya pekerjaan tetap dan menikah, pak”. “Hanya itu?” Ia menjawab “kalau keinginan sih banyak pak”. “Coba sebutkan”. “Saya ingin punya rumah sendiri, punya mobil, dan bisa membiayai orang tua berangkat ibadah haji”. “Lalu, apa itu mustahil?”. “Yah, sepertinya tidak mungkin pak. Sekarang saja saya masih baru mencari pekerjaan”.
Impian itu adalah bentuk visualisasi dari keinginan, cita-cita atau tujuan kita. Lha bagaimana bisa sampai pada keinginan atau cita-cita jikalau kita tidak pernah bisa memimpikannya. Tidak pernah mampu memvisualkannya. Bagaimana kita bisa menginginkan dapat mobil jika kita tidak pernah punya gambaran mobil itu seperti apa. Bagaimana kita bisa mendapatkan istri yang cantik, misalnya, jika kita sama sekali tidak punya gambaran tentang kecantikan.
Banyak orang sukses menasehati, untuk berhasil anda harus terlebih dahulu memimpikan keberhasilan itu, kemudian anda harus meyakini bahwa keberhasilan itu bisa diraih, lalu… raihlah. Simpel bukan?
Jadi kenapa takut bermimpi? Bermimpilah!
PILONIAN (1)
PILONIAN (1)
(Ray Asmoro)
Sariman menggaruk-garuk kepalanya padahal ia tidak ketombean. Itu hanya sebuah ekspresi dari kegelisahan yang tak pernah ia sangka-sangka akan datang dan hinggap di kepalanya. Persoalanya adalah karena Sariman mempertanyakan keputusannya untuk menikah tiga tahun lalu. “Apakah saya sudah memutuskan sesuatu yang benar?” “Benar nggak sih?” “Jangan-jangan saya salah” “Kalau benar, kenapa saya sekarang merasa tertekan?” dan masih banyak lagi pertanyaan yang hilir-mudik, tumpang-tindih dalam kesadarannya.
Oalah, Man… setelah tiga tahun kamu jalani bahtera rumah tanggamu, kenapa baru sekarang kamu mempertanyakan benar-salahnya keputusan yang kau ambil? Kamu ini nggak waras atau pilon sih?
Ceritanya begini. Sariman ini orangnya keren, wajahnya ganteng, tubuhnya cukup atletis, dan orangnya cukup supel. Entah mengapa ia tidak memilih menjadi coverboy atau bintang sinetron.
Sudah menjadi resikonya Sariman yang ganteng dan macho, selalu di dekati oleh perempuan-perempuan. Kalau pria-pria lain harus berjuang keras dan menyusun rencana, strategi bahkan akal-bulus untuk dapat dekat dengan perempuan, Sariman justru kebalikannya. Itulah resikonya menjadi Sariman. Ada yang sekedar menjadikan Sariman teman ngobrol atau curhat. Ada juga yang mendambakan cinta sejatinya dan ingin dilamar Sariman, bahkan ada yang ingin mengajak check-in di hotel. Pokoknya macam-macamlah kemauan perempuan-perempuan itu kepada Sariman kita ini.
Saya tidak heran, gimana perempuan-perempuan itu tidak terkiwir-kiwir oleh Sariman, lha wong Sariman itu jelmaan Arjuna. Dia penuh kelembutan, mengerti dan paham bagaimana memperlakukan orang lain sehingga merasa senang dan nyaman. Dia juga sangat santun, dia pandai memilih dan meronce kata-kata sehingga kalaupun dia mengkritik seseorang, yang di kritik tidak merasa salah dan sakit hati. Kalau dia menasehati, yang di nasehati tidak merasa direndahkan atau di gurui. Kalau dia memuji… Wah kalau soal memuji, Sarimanlah jawaranya. Pujiannya mampu membuat orang merasa tubuhnya menjadi ringan, seringan kapas, lalu melayang-layang ke angkasa.
Ketika hendak menikah, itu saat-saat yang sulit bagi Sariman. Sebenarnya kalau mau jujur Sariman belum sepenuhnya siap menikah. Dia masih sangat menikmati kebahagiaannya sebagai jomblo. Tapi toh akhirnya dia menikah juga.
Setidaknya ada tiga alasan utama dia menikah. Pertama, karena desakan dari orang tuanya. Mereka kan sudah sepuh dan belum memiliki cucu, sehingga setiap saat orang tua Sariman selalu bertanya “Man… kapan kamu menikah?” bahkan pernah suatu ketika orang tuanya memohon-mohon sambil menangis agar Sariman segera menikah, “Man… orang tuamu ini sudah pada tua, sebentar lagi pikun dan mati. Kamu kan sudah dewasa dan punya pekerjaan, kami tidak meminta balas budi apapun dari kamu Man, kami sudah sangat bahagia kalau kamu mau segera menikah dan memberikan kami cucu” begitu pinta orang tuanya sambil terisak-isak.
Alasan kedua, teman-teman sebaya Sariman rata-rata sudah menikah dan sudah punya dua anak. Usia Sariman saat itu sudah 32 tahun. Dia sering disindir teman-temannya “Man, segeralah kau menikah, usia kau sudah 32. Keburu tua kau nanti. Anak kau masih kecil, kau sudah bongkok” ada yang lebih parah, “Man, ente ini hanya menang tampang doang, tapi nggak punya nyali. Jangan-jangan ente impoten ya”
Nah, alasan ketiga adalah pure alasan spiritual. (Busyet!) Eit…jangan salah, Sariman kita ini walaupun gaul dan kadang sangat funky tapi kesadaran spiritualnya tidak cetek (mudah-mudahan). Memang sih, sholatnya masih bolong-bolong. Tapi dia punya jawabannya sendiri mengapa begitu.
“Sholat itu kan intinya berserah diri kepada Tuhan, memuja, berdoa, membangun komunikasi dua arah yang mesra dengan sang Khaliq dan saya melakukannya dalam bentuk lain” katanya. “Sebagai bentuk penyerahan diri dan dzikir saya kepada Tuhan, saya berusaha membantu orang lain, menyantuni anak-anak yatim dan anak-anak jalanan, saya mengabarkan kebaikan kepada setiap orang. Menjumpai Tuhan itu kan tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan itu kan ada dimana-mana, katanya Tuhan itu bersama orang-orang miskin dan papa, bersama orang-orang yang menderita dan teraniaya, lha kalau saya bersama mereka, membantu mereka, berbaur dan menghibur mereka berarti saya sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Sampeyan kan seringkali menyaksikan sendiri, ada orang sholatnya rajin, puasanya rajin, pergi haji berkali-kali seolah dia yang paling alim dan paling dekat dengan Tuhan, tapi malah gagap dalam bermasyarakat, bicaranya menyakitkan, tamak dan korup, hobi menebar fitnah, hatinya selalu penuh iri dan dengki. Apa namanya itu kalau bukan pilon?”
Anda nggak perlu sewot mendengar celoteh Sariman itu. Anda boleh setuju atau tidak. Kalau anda tidak sepaham dengan Sariman, itu hak anda. Tapi hak Sariman juga untuk menentukan bentuk dan laku spiritualnya. Biarlah itu menjadi urusan Sariman dengan Tuhannya. Sariman juga tidak pernah memaksa anda untuk setuju, kan? Jadi ya saran saya kita hargai saja pilihan Sariman sebagaimana dia juga tidak pernah mengutak-utik pilihan kita. Kalau dia salah, ya biar Tuhan saja yang menegurnya dengan caranya sendiri. Kalau kita mendebat Sariman, jangan-jangan kita lah yang pilon. Yang waras ngalah.
Kembali soal alasan ketiga tadi. Walaupun dia tidak pernah nyantri tapi dia tahu bahwa menikah dan memiliki keturunan itu bagian dari ibadah. Sariman bisa menunjukkan ayatnya dalam kitab suci bahkan mampu melafadzkannya dengan tartil. Disebut dalam ayat itu bahwa hukumnya wajib bagi yang mampu.
Lha Sariman ini kan termasuk orang yang “mampu”. Ia bukan budak, merdeka. Ia memiliki penghasilan yang layak. Usianya sudah 32 tahun, lebih dari usia akil balig. Dan yang penting, ia tidak mengalami disfungsi seksual, buktinya selalu setiap bangun pagi dia merasa heran, “padahal saya tidur sendirian lho, tapi kok selalu bangunnya berdua” (Dasar pilon lu Man!).
Karena ketiga alasan itulah Sariman memutuskan untuk mencari, memilih pasangan hidupnya dan menikah. Setelah menimbang-nimbang dari sekian banyak kandidat, ditetapkanlah nama Kastini sebagai yang terpilih jadi calon istrinya. Mengapa Kastini? Sariman memiliki alasan tersendiri, karena Kastini memenuhi kriteria pasangan ideal bagi Sariman.
Singkat cerita Sariman menikahi Kastini. Di tahun-tahun awal pernikahan kebahagiaan menyelimuti, hangat. Begitu memasuki usia pernikahan tahun ketiga, Sariman merasa hampa. Kebahagiaan yang pernah ia kecap terasa maya, bahkan hubungan suami-istri dilakukannya hanya sebatas “kewajiban”, Sariman tidak lagi merasakan sensasinya seperti ditahun-tahun awal pernikahan.
Lantas ia sering bertanya-tanya pada dirinya sendiri, “Apakah dulu saya sudah memutuskan sesuatu yang benar?” “Benar nggak sih?” “Jangan-jangan saya salah” “Kalau benar, kenapa saya sekarang merasa tertekan dan hampa?”
Menurut saya, soal ini Sariman benar-benar pilon. Sebelum memutuskan menikah, sehrusnya kan mikir dulu, dasar motivasinya apa, tujuannya apa, harus ada common goalsnya, targetnya apa, action plan-nya apa dan pada nilai-nilai apa pondasi rumah tangga akan dibangun.
“Wah, seperti mau jalankan perusahaan saja” kata Sariman.
Lho, apa bedanya? Mungkin dia punya motivasi yang kuat, tujuan yang jelas, target yang terarah, punya action plan, tapi kalau nilai-nilai yang dipegang lemah, ya tetap saja goyah. Semua yang dia punya tidak diletakkan pada nilai-nilai luhur, misalnya keterbukaan, pengertian dan penerimaan secara ikhlas, saling mendukung dan saling melengkapi, berkata dan bertindak terpuji, kejujuran, rasa syukur atau nilai-nilai lainnya yang disepakati bersama.
Rumah tangga memang seperti sebuah perusahaan. Coba pikir, membangun rumah tangga itu kan juga butuh modal. Ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan misalnya, biaya pinangan dan seserahan, biaya resepsi pernikahan, biaya administratif, dan lain-lainnya itu. Itu baru modal materi, belum modal goodwill seperti cinta dan kepercayaan. Selain modal, perlu juga kejelasan domisili. Kalau belum mampu beli rumah sendiri, minimal kontrak atau numpang orang tua. Kemudian butuh sistem yang jelas. Apa hak dan kewajiban kepala rumah tangga, apa hak dan kewajiban ibu rumah tangga, siapa yang berhak mengatur cashflow keuangan rumah tangga dan sebagainya.
Oalaah, Man..Man…
(Ray Asmoro)
Sariman menggaruk-garuk kepalanya padahal ia tidak ketombean. Itu hanya sebuah ekspresi dari kegelisahan yang tak pernah ia sangka-sangka akan datang dan hinggap di kepalanya. Persoalanya adalah karena Sariman mempertanyakan keputusannya untuk menikah tiga tahun lalu. “Apakah saya sudah memutuskan sesuatu yang benar?” “Benar nggak sih?” “Jangan-jangan saya salah” “Kalau benar, kenapa saya sekarang merasa tertekan?” dan masih banyak lagi pertanyaan yang hilir-mudik, tumpang-tindih dalam kesadarannya.
Oalah, Man… setelah tiga tahun kamu jalani bahtera rumah tanggamu, kenapa baru sekarang kamu mempertanyakan benar-salahnya keputusan yang kau ambil? Kamu ini nggak waras atau pilon sih?
Ceritanya begini. Sariman ini orangnya keren, wajahnya ganteng, tubuhnya cukup atletis, dan orangnya cukup supel. Entah mengapa ia tidak memilih menjadi coverboy atau bintang sinetron.
Sudah menjadi resikonya Sariman yang ganteng dan macho, selalu di dekati oleh perempuan-perempuan. Kalau pria-pria lain harus berjuang keras dan menyusun rencana, strategi bahkan akal-bulus untuk dapat dekat dengan perempuan, Sariman justru kebalikannya. Itulah resikonya menjadi Sariman. Ada yang sekedar menjadikan Sariman teman ngobrol atau curhat. Ada juga yang mendambakan cinta sejatinya dan ingin dilamar Sariman, bahkan ada yang ingin mengajak check-in di hotel. Pokoknya macam-macamlah kemauan perempuan-perempuan itu kepada Sariman kita ini.
Saya tidak heran, gimana perempuan-perempuan itu tidak terkiwir-kiwir oleh Sariman, lha wong Sariman itu jelmaan Arjuna. Dia penuh kelembutan, mengerti dan paham bagaimana memperlakukan orang lain sehingga merasa senang dan nyaman. Dia juga sangat santun, dia pandai memilih dan meronce kata-kata sehingga kalaupun dia mengkritik seseorang, yang di kritik tidak merasa salah dan sakit hati. Kalau dia menasehati, yang di nasehati tidak merasa direndahkan atau di gurui. Kalau dia memuji… Wah kalau soal memuji, Sarimanlah jawaranya. Pujiannya mampu membuat orang merasa tubuhnya menjadi ringan, seringan kapas, lalu melayang-layang ke angkasa.
Ketika hendak menikah, itu saat-saat yang sulit bagi Sariman. Sebenarnya kalau mau jujur Sariman belum sepenuhnya siap menikah. Dia masih sangat menikmati kebahagiaannya sebagai jomblo. Tapi toh akhirnya dia menikah juga.
Setidaknya ada tiga alasan utama dia menikah. Pertama, karena desakan dari orang tuanya. Mereka kan sudah sepuh dan belum memiliki cucu, sehingga setiap saat orang tua Sariman selalu bertanya “Man… kapan kamu menikah?” bahkan pernah suatu ketika orang tuanya memohon-mohon sambil menangis agar Sariman segera menikah, “Man… orang tuamu ini sudah pada tua, sebentar lagi pikun dan mati. Kamu kan sudah dewasa dan punya pekerjaan, kami tidak meminta balas budi apapun dari kamu Man, kami sudah sangat bahagia kalau kamu mau segera menikah dan memberikan kami cucu” begitu pinta orang tuanya sambil terisak-isak.
Alasan kedua, teman-teman sebaya Sariman rata-rata sudah menikah dan sudah punya dua anak. Usia Sariman saat itu sudah 32 tahun. Dia sering disindir teman-temannya “Man, segeralah kau menikah, usia kau sudah 32. Keburu tua kau nanti. Anak kau masih kecil, kau sudah bongkok” ada yang lebih parah, “Man, ente ini hanya menang tampang doang, tapi nggak punya nyali. Jangan-jangan ente impoten ya”
Nah, alasan ketiga adalah pure alasan spiritual. (Busyet!) Eit…jangan salah, Sariman kita ini walaupun gaul dan kadang sangat funky tapi kesadaran spiritualnya tidak cetek (mudah-mudahan). Memang sih, sholatnya masih bolong-bolong. Tapi dia punya jawabannya sendiri mengapa begitu.
“Sholat itu kan intinya berserah diri kepada Tuhan, memuja, berdoa, membangun komunikasi dua arah yang mesra dengan sang Khaliq dan saya melakukannya dalam bentuk lain” katanya. “Sebagai bentuk penyerahan diri dan dzikir saya kepada Tuhan, saya berusaha membantu orang lain, menyantuni anak-anak yatim dan anak-anak jalanan, saya mengabarkan kebaikan kepada setiap orang. Menjumpai Tuhan itu kan tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan itu kan ada dimana-mana, katanya Tuhan itu bersama orang-orang miskin dan papa, bersama orang-orang yang menderita dan teraniaya, lha kalau saya bersama mereka, membantu mereka, berbaur dan menghibur mereka berarti saya sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Sampeyan kan seringkali menyaksikan sendiri, ada orang sholatnya rajin, puasanya rajin, pergi haji berkali-kali seolah dia yang paling alim dan paling dekat dengan Tuhan, tapi malah gagap dalam bermasyarakat, bicaranya menyakitkan, tamak dan korup, hobi menebar fitnah, hatinya selalu penuh iri dan dengki. Apa namanya itu kalau bukan pilon?”
Anda nggak perlu sewot mendengar celoteh Sariman itu. Anda boleh setuju atau tidak. Kalau anda tidak sepaham dengan Sariman, itu hak anda. Tapi hak Sariman juga untuk menentukan bentuk dan laku spiritualnya. Biarlah itu menjadi urusan Sariman dengan Tuhannya. Sariman juga tidak pernah memaksa anda untuk setuju, kan? Jadi ya saran saya kita hargai saja pilihan Sariman sebagaimana dia juga tidak pernah mengutak-utik pilihan kita. Kalau dia salah, ya biar Tuhan saja yang menegurnya dengan caranya sendiri. Kalau kita mendebat Sariman, jangan-jangan kita lah yang pilon. Yang waras ngalah.
Kembali soal alasan ketiga tadi. Walaupun dia tidak pernah nyantri tapi dia tahu bahwa menikah dan memiliki keturunan itu bagian dari ibadah. Sariman bisa menunjukkan ayatnya dalam kitab suci bahkan mampu melafadzkannya dengan tartil. Disebut dalam ayat itu bahwa hukumnya wajib bagi yang mampu.
Lha Sariman ini kan termasuk orang yang “mampu”. Ia bukan budak, merdeka. Ia memiliki penghasilan yang layak. Usianya sudah 32 tahun, lebih dari usia akil balig. Dan yang penting, ia tidak mengalami disfungsi seksual, buktinya selalu setiap bangun pagi dia merasa heran, “padahal saya tidur sendirian lho, tapi kok selalu bangunnya berdua” (Dasar pilon lu Man!).
Karena ketiga alasan itulah Sariman memutuskan untuk mencari, memilih pasangan hidupnya dan menikah. Setelah menimbang-nimbang dari sekian banyak kandidat, ditetapkanlah nama Kastini sebagai yang terpilih jadi calon istrinya. Mengapa Kastini? Sariman memiliki alasan tersendiri, karena Kastini memenuhi kriteria pasangan ideal bagi Sariman.
Singkat cerita Sariman menikahi Kastini. Di tahun-tahun awal pernikahan kebahagiaan menyelimuti, hangat. Begitu memasuki usia pernikahan tahun ketiga, Sariman merasa hampa. Kebahagiaan yang pernah ia kecap terasa maya, bahkan hubungan suami-istri dilakukannya hanya sebatas “kewajiban”, Sariman tidak lagi merasakan sensasinya seperti ditahun-tahun awal pernikahan.
Lantas ia sering bertanya-tanya pada dirinya sendiri, “Apakah dulu saya sudah memutuskan sesuatu yang benar?” “Benar nggak sih?” “Jangan-jangan saya salah” “Kalau benar, kenapa saya sekarang merasa tertekan dan hampa?”
Menurut saya, soal ini Sariman benar-benar pilon. Sebelum memutuskan menikah, sehrusnya kan mikir dulu, dasar motivasinya apa, tujuannya apa, harus ada common goalsnya, targetnya apa, action plan-nya apa dan pada nilai-nilai apa pondasi rumah tangga akan dibangun.
“Wah, seperti mau jalankan perusahaan saja” kata Sariman.
Lho, apa bedanya? Mungkin dia punya motivasi yang kuat, tujuan yang jelas, target yang terarah, punya action plan, tapi kalau nilai-nilai yang dipegang lemah, ya tetap saja goyah. Semua yang dia punya tidak diletakkan pada nilai-nilai luhur, misalnya keterbukaan, pengertian dan penerimaan secara ikhlas, saling mendukung dan saling melengkapi, berkata dan bertindak terpuji, kejujuran, rasa syukur atau nilai-nilai lainnya yang disepakati bersama.
Rumah tangga memang seperti sebuah perusahaan. Coba pikir, membangun rumah tangga itu kan juga butuh modal. Ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan misalnya, biaya pinangan dan seserahan, biaya resepsi pernikahan, biaya administratif, dan lain-lainnya itu. Itu baru modal materi, belum modal goodwill seperti cinta dan kepercayaan. Selain modal, perlu juga kejelasan domisili. Kalau belum mampu beli rumah sendiri, minimal kontrak atau numpang orang tua. Kemudian butuh sistem yang jelas. Apa hak dan kewajiban kepala rumah tangga, apa hak dan kewajiban ibu rumah tangga, siapa yang berhak mengatur cashflow keuangan rumah tangga dan sebagainya.
Oalaah, Man..Man…
IVONNE CAROLINA (cerpen)
IVONNE CAROLINA
Cerpen Ray Asmoro
Aku ada kenal dengan seorang perempuan. Ivonne Carolina namanya. Kepada teman-teman, aku selalu bercerita tentang dirinya. Tak habis-habis cerita yang ku buat. Selalu ada cerita baru tentang Ivonne Carolina, dan aku selalu menggambarkannya dengan sangat luar biasa, tanpa sedikitpun cela. Anehnya teman-temanku percaya sepenuhnya. Padahal sesungguhnya aku tidak pernah bertemu dengannya.
“Kamu kenal dimana?” tanya Arif suatu ketika.
Aku mengenal Ivonne Carolina, di hari pertama pada pergelaran pameran lukisan di sebuah galeri di Jakarta, kira-kira tiga jam setelah acara pembukaan. Puluhan bentuk lukisan ekspresionis (condong ke bentuk abstrak) dipajang disana. Aku sebenarnya tidak paham tentang lukisan, kecuali yang realis. Aku cuma tahu disitu ada coretan-coretan, goresan-goresan, kadang simetris, kadang tak beraturan dan (menurutku) cenderung ngawur. Kadang terlihat seperti api yang menyala-nyala tapi judulnya “Secuil Senja Yang Terlewatkan”. Aku benar-benar tidak habis pikir soal itu. Aku mencoba menikmatinya, dan entah mengapa aku selalu menyukai suasana yang terbangun di galeri dan di acara-acara kesenian lainnya.
Di depan Secuil Senja Yang Terlewatkan itulah aku bertemu Ivonne Carolina. Lukisan itu memang di pajang di tempat yang langsung terlihat mata ketika kita memasuki galeri itu. Saat aku masuk, tak banyak orang disana. Seorang perempuan muda berambut sebahu, dengan busana kasual, berdiri mematung di depan Secuil Senja Yang Terlewatkan. Akupun mendekati lukisan itu. Aku tidak tahu, mengapa aku tiba-tiba mendekati Secuil Senja Yang Terlewatkan, karena daya tarik lukisan atau karena ada perempuan itu, tidak jelas lagi bagiku mana yang lebih menarik. Lukisan atau perempuan.
Aku berdiri di sisi perempuan itu, di depan lukisan yang terlihat seperti luapan lidah api dengan warna merah, kuning dan biru dalam sebuah kombinasi yang unik.
“Mengapa ia melewatkan secuil senja kalau pada akhirnya di sesalinya.” Aku coba memancing obrolan dengan berlagak apresiatif.
“Ia memang melewatkan secuil senja, tapi ada sesuatu yang ia tangkap dari yang cuma secuil itu.” Komentarnya enteng, seperti yang aku harapkan.
“Kenapa harus senja?”
“Itu hanya persoalan waktu.”
“Tapi kenapa ia nampak begitu pesimis.”
“Bagiku itu justru nampak sebagai sebuah harapan atau… kerinduan, barangkali.”
Perbincangan kami terus berlanjut hingga pada beberapa lukisan berikutnya yang kami perhatikan. Setelah selesai mengamati lukisan-lukisan itu, aku menawarinya untuk minum bersama di kantin yang ada di sebelah galeri itu. Ia setuju. Di sanalah baru aku menanyakan namanya, setelah tenggorokan kami basah oleh es teh dalam kemasan botol. Bahkan sekarang aku tahu berapa nomor telepon selularnya.
* * *
“Benarkah?” tanya Timbul, kawanku, ketika mendengarkan cerita dariku tentang Ivonne Carolina untuk kesekian kalinya.
Benar. Tadi malam ia datang dalam mimpiku.
Kisahnya begini. Aku punya sebuah souvenir, hadiah dari temanku yang pernah melancong ke Eropa. Bentuknya seperti bola kaca, kecil. Didalamnya ada rumah dan pepohonan. Kalau bola kaca itu di goyang-goyang, serbuk putih didalamnya akan beterbangan seperti salju. Bola kaca itu aku letakkan diatas meja kamarku.
Anehnya, aku melihat Ivonne ada di dalam bola kaca itu.
Dengan jaket tebal, penutup kepala dan syal biru tua membalut leher serta sarung tangan berwarna gelap, ia berlari keluar dari rumah itu dengan sangat ketakutan dan panik. Dia berlari ke tengah hamparan salju. Setiap kali melangkah, kakinya ambles beberapa inci. Ketika bernapas, ada uap seperti asap knalpot keluar dari mulut dan hidungnya.
Seperti tak peduli dengan kebekuan, ia terus mencoba berlari ke samping rumah, lalu ke arah depan sambil memanggil namaku.
“Morgan…! Morgan…!” begitu teriaknya, berulang-ulang.
Kenapa ia memanggil aku? Apakah aku punya janji dengannya? Rasanya, aku tidak punya janji. Tapi kenapa dia memanggil namaku? Mungkinkah ada Morgan yang lain? Atau tadi sebelumnya, di rumah dalam bola kaca itu, dia tertidur dan bermimpi denganku, sebuah mimpi indah, dan ketika terbangun ia tidak mendapati aku di sisinya? Atau, apakah dia begitu merindukan aku disaat musim dingin seperti ini? Atau dia ketakutan berada dalam rumah itu sendirian, lalu ia ingin aku menemaninya?
Atau, tanpa aku tahu, tadi aku berkunjung ke rumahnya dalam bola kaca itu, lalu aku bercinta dengannya, kemudian aku meninggalkannya begitu saja? Atau, aku adalah lelakinya, dan sebelum dia pulang, aku menulis pesan pada secarik kertas yang berbunyi “Maaf, aku harus pergi. Duniamu terlalu sesak bagiku,” kemudian ku tempel kertas itu di pintu kulkas dan ketika pulang, dia membacanya dan merasa sangat kehilangan aku? Atau, aku telah membuatnya terluka, sehingga dia mencariku dengan niatan ingin mencekik leherku? Entahlah.
Yang kulihat kemudian, Ivonne menggedor kaca itu dengan tangannya dari dalam sambil memanggil namaku. “Morgan…! Morgan…!”
Aku dekati bola kaca itu. Aku menatapnya. Dia tampak sangat sedih dan menghiba. Bibirnya biru kedinginan. Wajahnya terlihat pucat.
“Keluarkan aku dari sini, Morgan,” pintanya.
“Bagaimana caranya aku mengeluarkanmu?” tanyaku.
“Pecahkan dinding kaca ini” katanya dengan penuh iba.
“Kalau ku pecahkan dinding kaca ini, kamu akan masuk dalam duniaku dan kamu akan kehilangan duniamu. Kamu tidak bisa membawa duniamu kedalam duniaku.”
Setelah mengatakan itu, aku terbangun dari mimpiku lantaran ada yang mengetuk pintu kamar dari luar.
Dengan kemalasan yang teramat sangat, aku bangkit dari tidur. Dan ketika pintu ku buka, aku mendapati Ivonne Carolina berdiri di depan pintu dengan sangat anggun. Rambutnya hitam menjuntai. Matanya yang teduh menatapku penuh hasrat sambil menggigit bibirnya. Ia begitu nyata, tidak lagi sekedar mimpi.
“Aku tidak salah kamar, kan?” katanya sambil senyum dan mengerdipkan sebelah matanya. Kegenitan yang syahdu.
* * *
Mmm… aku ada kenal dengan seorang perempuan. Ivonne Carolina namanya. Kepada teman-teman, aku selalu bercerita tentang dirinya. Tak ada habis-habis cerita yang ku buat. Selalu ada cerita baru tentang Ivonne Carolina. Aku selalu menggambarkannya dengan sangat luar biasa, tanpa sedikitpun cela. Padahal sesungguhnya aku tidak pernah bertemu dengannya.
“Ayolah. Sesekali, ajak dia kemari.” kata Arif.
“Nikahi saja dia,” saran Timbul suatu ketika.
Arif dan Timbul adalah dua orang temanku dari berpuluh-puluh temanku yang semuanya sering mendengar ceritaku tentang Ivonne Carolina. Aku selalu punya cerita baru yang sangat fantastis untuk mereka dengarkan. Dan mereka tidak tahu, semakin banyak cerita yang aku buat, aku juga semakin penasaran untuk bisa bertemu dengannya.
* * *
Ya, ya. Aku ada kenal dengan seorang perempuan. Ivonne Carolina namanya. Kepada teman-teman, aku selalu bercerita tentang dirinya. Tak habis-habis cerita yang ku buat. Selalu ada cerita baru tentang Ivonne Carolina. Padahal sesungguhnya aku tidak pernah bertemu dengannya. Tapi aku benar-benar mengenalnya. Tidak perlu diragukan lagi soal itu. Dan cerita sesungguhnya tentang Ivonne Carolina, tetap aku rahasiakan, karena ia pun masih jadi teka-teki bagiku.
[Menteng, 08.10.02 ; 02.42wib]
Cerpen Ray Asmoro
Aku ada kenal dengan seorang perempuan. Ivonne Carolina namanya. Kepada teman-teman, aku selalu bercerita tentang dirinya. Tak habis-habis cerita yang ku buat. Selalu ada cerita baru tentang Ivonne Carolina, dan aku selalu menggambarkannya dengan sangat luar biasa, tanpa sedikitpun cela. Anehnya teman-temanku percaya sepenuhnya. Padahal sesungguhnya aku tidak pernah bertemu dengannya.
“Kamu kenal dimana?” tanya Arif suatu ketika.
Aku mengenal Ivonne Carolina, di hari pertama pada pergelaran pameran lukisan di sebuah galeri di Jakarta, kira-kira tiga jam setelah acara pembukaan. Puluhan bentuk lukisan ekspresionis (condong ke bentuk abstrak) dipajang disana. Aku sebenarnya tidak paham tentang lukisan, kecuali yang realis. Aku cuma tahu disitu ada coretan-coretan, goresan-goresan, kadang simetris, kadang tak beraturan dan (menurutku) cenderung ngawur. Kadang terlihat seperti api yang menyala-nyala tapi judulnya “Secuil Senja Yang Terlewatkan”. Aku benar-benar tidak habis pikir soal itu. Aku mencoba menikmatinya, dan entah mengapa aku selalu menyukai suasana yang terbangun di galeri dan di acara-acara kesenian lainnya.
Di depan Secuil Senja Yang Terlewatkan itulah aku bertemu Ivonne Carolina. Lukisan itu memang di pajang di tempat yang langsung terlihat mata ketika kita memasuki galeri itu. Saat aku masuk, tak banyak orang disana. Seorang perempuan muda berambut sebahu, dengan busana kasual, berdiri mematung di depan Secuil Senja Yang Terlewatkan. Akupun mendekati lukisan itu. Aku tidak tahu, mengapa aku tiba-tiba mendekati Secuil Senja Yang Terlewatkan, karena daya tarik lukisan atau karena ada perempuan itu, tidak jelas lagi bagiku mana yang lebih menarik. Lukisan atau perempuan.
Aku berdiri di sisi perempuan itu, di depan lukisan yang terlihat seperti luapan lidah api dengan warna merah, kuning dan biru dalam sebuah kombinasi yang unik.
“Mengapa ia melewatkan secuil senja kalau pada akhirnya di sesalinya.” Aku coba memancing obrolan dengan berlagak apresiatif.
“Ia memang melewatkan secuil senja, tapi ada sesuatu yang ia tangkap dari yang cuma secuil itu.” Komentarnya enteng, seperti yang aku harapkan.
“Kenapa harus senja?”
“Itu hanya persoalan waktu.”
“Tapi kenapa ia nampak begitu pesimis.”
“Bagiku itu justru nampak sebagai sebuah harapan atau… kerinduan, barangkali.”
Perbincangan kami terus berlanjut hingga pada beberapa lukisan berikutnya yang kami perhatikan. Setelah selesai mengamati lukisan-lukisan itu, aku menawarinya untuk minum bersama di kantin yang ada di sebelah galeri itu. Ia setuju. Di sanalah baru aku menanyakan namanya, setelah tenggorokan kami basah oleh es teh dalam kemasan botol. Bahkan sekarang aku tahu berapa nomor telepon selularnya.
* * *
“Benarkah?” tanya Timbul, kawanku, ketika mendengarkan cerita dariku tentang Ivonne Carolina untuk kesekian kalinya.
Benar. Tadi malam ia datang dalam mimpiku.
Kisahnya begini. Aku punya sebuah souvenir, hadiah dari temanku yang pernah melancong ke Eropa. Bentuknya seperti bola kaca, kecil. Didalamnya ada rumah dan pepohonan. Kalau bola kaca itu di goyang-goyang, serbuk putih didalamnya akan beterbangan seperti salju. Bola kaca itu aku letakkan diatas meja kamarku.
Anehnya, aku melihat Ivonne ada di dalam bola kaca itu.
Dengan jaket tebal, penutup kepala dan syal biru tua membalut leher serta sarung tangan berwarna gelap, ia berlari keluar dari rumah itu dengan sangat ketakutan dan panik. Dia berlari ke tengah hamparan salju. Setiap kali melangkah, kakinya ambles beberapa inci. Ketika bernapas, ada uap seperti asap knalpot keluar dari mulut dan hidungnya.
Seperti tak peduli dengan kebekuan, ia terus mencoba berlari ke samping rumah, lalu ke arah depan sambil memanggil namaku.
“Morgan…! Morgan…!” begitu teriaknya, berulang-ulang.
Kenapa ia memanggil aku? Apakah aku punya janji dengannya? Rasanya, aku tidak punya janji. Tapi kenapa dia memanggil namaku? Mungkinkah ada Morgan yang lain? Atau tadi sebelumnya, di rumah dalam bola kaca itu, dia tertidur dan bermimpi denganku, sebuah mimpi indah, dan ketika terbangun ia tidak mendapati aku di sisinya? Atau, apakah dia begitu merindukan aku disaat musim dingin seperti ini? Atau dia ketakutan berada dalam rumah itu sendirian, lalu ia ingin aku menemaninya?
Atau, tanpa aku tahu, tadi aku berkunjung ke rumahnya dalam bola kaca itu, lalu aku bercinta dengannya, kemudian aku meninggalkannya begitu saja? Atau, aku adalah lelakinya, dan sebelum dia pulang, aku menulis pesan pada secarik kertas yang berbunyi “Maaf, aku harus pergi. Duniamu terlalu sesak bagiku,” kemudian ku tempel kertas itu di pintu kulkas dan ketika pulang, dia membacanya dan merasa sangat kehilangan aku? Atau, aku telah membuatnya terluka, sehingga dia mencariku dengan niatan ingin mencekik leherku? Entahlah.
Yang kulihat kemudian, Ivonne menggedor kaca itu dengan tangannya dari dalam sambil memanggil namaku. “Morgan…! Morgan…!”
Aku dekati bola kaca itu. Aku menatapnya. Dia tampak sangat sedih dan menghiba. Bibirnya biru kedinginan. Wajahnya terlihat pucat.
“Keluarkan aku dari sini, Morgan,” pintanya.
“Bagaimana caranya aku mengeluarkanmu?” tanyaku.
“Pecahkan dinding kaca ini” katanya dengan penuh iba.
“Kalau ku pecahkan dinding kaca ini, kamu akan masuk dalam duniaku dan kamu akan kehilangan duniamu. Kamu tidak bisa membawa duniamu kedalam duniaku.”
Setelah mengatakan itu, aku terbangun dari mimpiku lantaran ada yang mengetuk pintu kamar dari luar.
Dengan kemalasan yang teramat sangat, aku bangkit dari tidur. Dan ketika pintu ku buka, aku mendapati Ivonne Carolina berdiri di depan pintu dengan sangat anggun. Rambutnya hitam menjuntai. Matanya yang teduh menatapku penuh hasrat sambil menggigit bibirnya. Ia begitu nyata, tidak lagi sekedar mimpi.
“Aku tidak salah kamar, kan?” katanya sambil senyum dan mengerdipkan sebelah matanya. Kegenitan yang syahdu.
* * *
Mmm… aku ada kenal dengan seorang perempuan. Ivonne Carolina namanya. Kepada teman-teman, aku selalu bercerita tentang dirinya. Tak ada habis-habis cerita yang ku buat. Selalu ada cerita baru tentang Ivonne Carolina. Aku selalu menggambarkannya dengan sangat luar biasa, tanpa sedikitpun cela. Padahal sesungguhnya aku tidak pernah bertemu dengannya.
“Ayolah. Sesekali, ajak dia kemari.” kata Arif.
“Nikahi saja dia,” saran Timbul suatu ketika.
Arif dan Timbul adalah dua orang temanku dari berpuluh-puluh temanku yang semuanya sering mendengar ceritaku tentang Ivonne Carolina. Aku selalu punya cerita baru yang sangat fantastis untuk mereka dengarkan. Dan mereka tidak tahu, semakin banyak cerita yang aku buat, aku juga semakin penasaran untuk bisa bertemu dengannya.
* * *
Ya, ya. Aku ada kenal dengan seorang perempuan. Ivonne Carolina namanya. Kepada teman-teman, aku selalu bercerita tentang dirinya. Tak habis-habis cerita yang ku buat. Selalu ada cerita baru tentang Ivonne Carolina. Padahal sesungguhnya aku tidak pernah bertemu dengannya. Tapi aku benar-benar mengenalnya. Tidak perlu diragukan lagi soal itu. Dan cerita sesungguhnya tentang Ivonne Carolina, tetap aku rahasiakan, karena ia pun masih jadi teka-teki bagiku.
[Menteng, 08.10.02 ; 02.42wib]
Langganan:
Postingan (Atom)










.jpg)